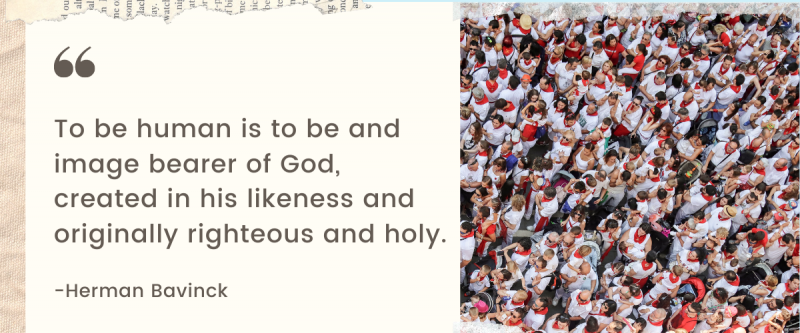
Human aren't god, but created to become God's representation to the world.
“Siapakah manusia itu?”
Setiap orang tentu memiliki pandangannya masing-masing mengenai hal tersebut, begitu pula dengan saya. Tapi di sisi lain, saya juga ingin tahu pemikiran orang lain tentang identitas diri manusia yang sebenarnya—baik di mata Sang Pencipta maupun di mata sesamanya. Karena itu, saya menanyakannya di Instagram—dan setidaknya menemukan dua jawaban yang unik bagi saya:
“Makhluk hidup paling lemah, tetapi beruntung karena memiliki perkembangan logika.”
“”Binatang” yang berhasrat, mendamba, dan imajinatif”, kalau kata James K. A. Smith.”
Sejak di bangku sekolah (mungkin bahkan saat masih SD), kita pernah mendengar bahwa spesies manusia yang ada saat ini—manusia modern—disebut Homo sapiens. Tapi kalau melihat dari teori evolusi, kita akan mengetahui bahwa ternyata ada beberapa spesies manusia lain yang ada di zaman purba. Sebagian di antaranya adalah Homo soloensis (manusia dari Lembah Solo), Homo florensis (dari Flores), Homo erectus (dari Asia Timur), Homo rudolensis (dari Afrika Timur), dan Homo neanderthalensis (dari Eropa dan Asia Barat).[1] Namun dalam artikel ini, kita hanya akan berfokus pada pembahasan mengenai Homo sapiens dan bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai makhluk hidup yang “modern” (jadi saya nggak akan membahas tentang evolusi lebih jauh HEHE). Yes, teori evolusi justru bisa membuat kita menyadari bahwa ada Allah, Sang Pencipta, yang menciptakan ragam spesies makhluk hidup—saking uniknya mereka, kan?
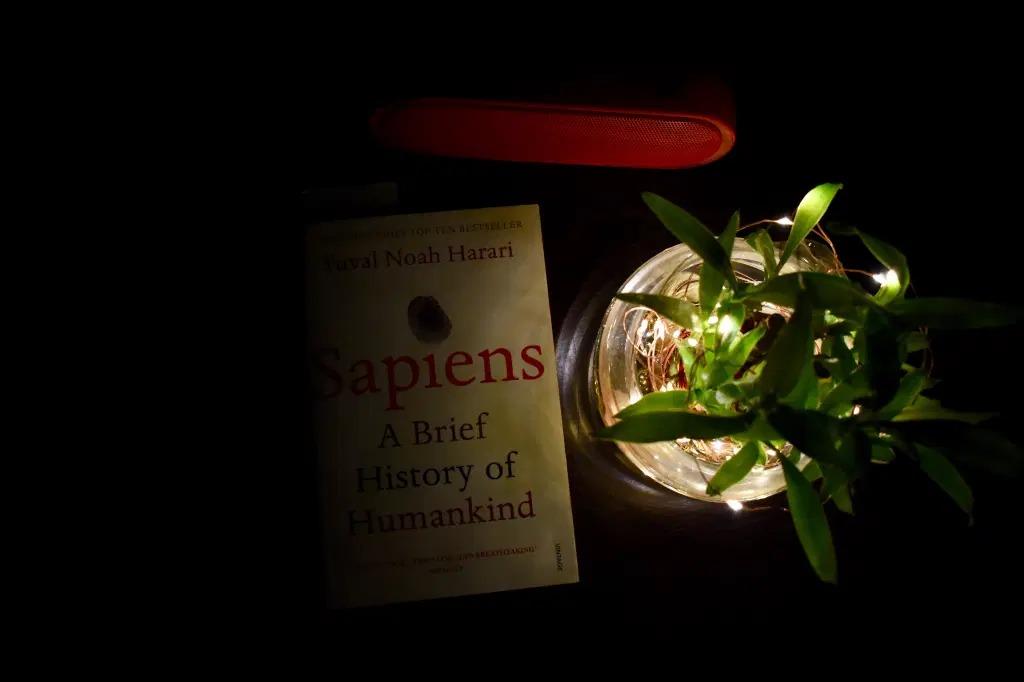
Menurut bahasa aslinya, Homo sapiens berarti “manusia yang bijak” (“Homo” adalah bahasa Latin untuk “manusia” dan “sapiens” untuk “bijak”).[2] Manusia modern disebut demikian karena mereka (termasuk kita yang hidup di zaman sekarang) memiliki perkembangan dalam banyak aspek kehidupan—yang membuatnya jauh berbeda kalau dibandingkan dengan berbagai spesies manusia lainnya. Perkembangan yang dimaksud juga termasuk dalam hal pola pikir, sehingga kita bisa memikirkan dan melakukan banyak hal yang spektakuler—yang mungkin tidak pernah dibayangkan berpuluh-puluh ribu tahun sebelumnya. Kita tidak lagi hanya bergerak berdasarkan survival instinc, tapi juga memakai logika untuk memperhitungkan risiko yang bisa terjadi setelah kita mengambil sebuah keputusan. Bahkan filsuf Inggris di abad ke-17 yang bernama John Locke menyatakan bahwa “infants are born knowing nothing and that all knowledge is acquired through sensory experiences, behaviorism stated that environment and its associated effects on animals were the sole determinants of learning.”[3] Teori yang dikenal dengan “tabula rasa” tersebut seolah-olah ingin menunjukkan bagaimana manusia terlahir seperti kertas putih yang kosong, dan membutuhkan lingkungan sebagai sumber pengetahuan mereka. Wah… Kelihatannya setiap bayi yang lahir memang sepolos itu, kan? Tapi sayangnya, kenyataannya tidaklah seindah itu:
Natur manusia yang sesungguhnya sebagai gambar dan rupa Allah (imago Dei – bahasa Yunani) sudah rusak karena dosa, bahkan sejak sebelum mereka terlahir ke dunia.
Pernyataan di atas bukan berarti manusia adalah ciptaan yang gagal. Nggak gitu. Bahkan di Kejadian 1:26-31, Allah sendiri yang berinisiatif untuk menciptakan manusia. Kalau Allah adalah Pribadi yang sempurna menciptakan sesuatu yang corrupted, maka Dia bukanlah Allah yang sempurna. Plus, di ayat ke-31a dikatakan, “Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu sungguh amat baik.” Kalimat tersebut berbeda dari saat Allah baru menciptakan langit dan bumi serta isinya, namun belum ada manusia di dalamnya. Namun setelah manusia diciptakan dan diberi mandat budaya (beranak cucu dan memenuhi bumi serta mengelolanya untuk memuliakan Tuhan), barulah dikatakan “Allah melihat semua yang dijadikan-Nya itu sungguh amat baik”. Kenapa bisa begitu? Apakah itu artinya tumbuhan seperti Rafflesia arnoldi dan hewan seperti kucing yang suka mengobrak-abrik tong sampah tidaklah dipandang baik menurut Sang Pencipta?
Hmmm…. Apa yang membedakan manusia dari ciptaan lain adalah karena pada dasarnya, manusia diciptakan menurut gambar (tselem – bahasa Ibrani) dan rupa (demuth – bahasa Ibrani) Allah. Well, selain manusia, tidak ada ciptaan lain yang dibuat dengan cara yang sama. Okelah, sebelum menciptakan manusia, memang ada frase “Berfirmanlah Allah”—sama seperti ciptaan-ciptaan yang lain. Namun menurut Bavinck, “Animals were brought forth by the earth at God’s Command; humanity, however, was created, after divine deliberation, in God’s image, to be master over all things.”[4] Artinya, hanya manusia yang diciptakan melalui bentukan tangan Allah sendiri sesuai gambar dan rupa-Nya, diberikan napas kehidupan oleh-Nya, dan memiliki mandat untuk mengelola bumi dan seluruh isinya. Selain itu, Allah Tritunggal berunding terlebih dulu (ada kata “Kita” di Kejadian 1:26, menandakan Sang Pencipta, Sang Firman, dan Roh Allah). Ketiga hal tersebut membuktikan bahwa manusia diciptakan dengan sangat istimewa—apalagi karena mereka dibekali dengan kemampuan berpikir dan akses untuk mengenal Allah secara terbuka. Kapanpun mau, mereka bisa berbicara (bahkan berdiskusi kali, ya?) kepada-Nya. Yes, God gives human freewill to do everything, for He didn’t created them to become robots.

Setidaknya sampai di titik ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada dua hal yang ditekankan pada Kejadian 1-2:
1. Manusia bukan Allah
Menurut tradisi Yahudi (dan yang juga saya yakini), penulis kitab Kejadian adalah Musa, orang Lewi (salah satu suku Israel) yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Alasan Musa menegaskan poin pertama ini adalah karena dia ingin memberikan pandangan tentang Allah yang berkuasa (baca: pola teologi yang sebenarnya) kepada umat sebangsanya. Kesadaran (yang tentunya diilhami oleh Allah sendiri) ini muncul sebagai tanggapan atas pemahaman orang Israel yang terbentuk sejak mereka menjadi budak di Mesir. Kalau di sana mereka belajar bahwa bulan dan bintang harus disembah karena mereka adalah dewa, maka selama menuju ke Kanaan—Tanah Perjanjian—mereka ditekankan bahwa hanya Allah Sang Penciptalah yang patut disembah (bukannya dewa matahari atau bahkan Firaun)
2. Manusia dipilih untuk jadi simbol representasi Allah
Meskipun mungkin mudah bagi kita di zaman sekarang untuk memahami hal ini, nyatanya tidak demikian bagi orang Israel. Zaman dulu belum secanggih sekarang, Guys. Hehe. Karena itulah, Musa menggunakan konteks yang sangat dekat dengan orang Israel untuk memudahkan mereka dalam menangkap konsep tentang tselem dan demuth di atas. Sama seperti Sphinx yang menunjukkan bahwa Firaun adalah orang yang berkuasa di Mesir dan tidak ada yang bisa melawannya, kita—sebagai manusia—diciptakan secara khusus untuk menjadi display Allah. Display yang seperti apa? Mengutip Bavinck, “To be human is to be and image bearer of God, created in his likeness and originally righteous and holy.”[5] Dengan demikian, siapapun yang melihat kita—seharusnya—tahu SIAPA yang berkuasa: Allah Sang Pencipta, yang adil dan kudus.
Ketika kita berfungsi sebagaimana kita diciptakan, kita disebut sebagai anak-anak Allah, karena kita menggambarkan diri-Nya melalui kehidupan kita.
Well, tapi seperti yang sudah disampaikan di atas, natur manusia yang sempurna ini rusak karena dosa (Roma 3:23). Dosa membuat gambar dan rupa Allah yang sempurna menjadi rusak (teman-teman bisa melihat ilustrasinya di sini). Dengan freewill yang kita miliki, sebenarnya kita memiliki kapasitas untuk memilih antara menaati Tuhan atau mengikuti pemikiran diri sendiri untuk membuat standar baru mengenai apa yang disebut hal yang benar dan salah. Ironisnya, sekalipun diciptakan secara sempurna, kita bukanlah pencipta yang bisa memulihkan keadaan yang sudah tercemar dosa. Akibatnya tidak terhindarkan lagi: keinginan untuk memberontak pada Allah membawa kita melenceng dari tujuan semula—yaitu memuliakan Allah dan menikmati-Nya selamanya.
Jangankan memutuskan untuk bertobat, kita tidak akan pernah memikirkan tentang Allah kalau bukan karena inisiatif-Nya sendiri untuk menyelamatkan manusia (termasuk kita). Dari situlah gambar Allah dalam diri kita dipulihkan melalui keselamatan ilahi (Roma 8:29; 2 Korintus 3:18; Efesus 4:22-24; Kolose 3:9-10). Keselamatan tersebut bisa terjadi karena Allah mengirimkan Anak-Nya yang Tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita (bagian ini mungkin akan kita bahas dalam artikel berikutnya. So stay tuned!). Yaps, hanya Dialah gambar yang sejati dan sempurna dari Allah yang tidak kelihatan (Kolose 1:15)—sekaligus menjadi role model bagi kita untuk mengalami pemulihan gambar diri yang seutuhnya di dalam diri-Nya.
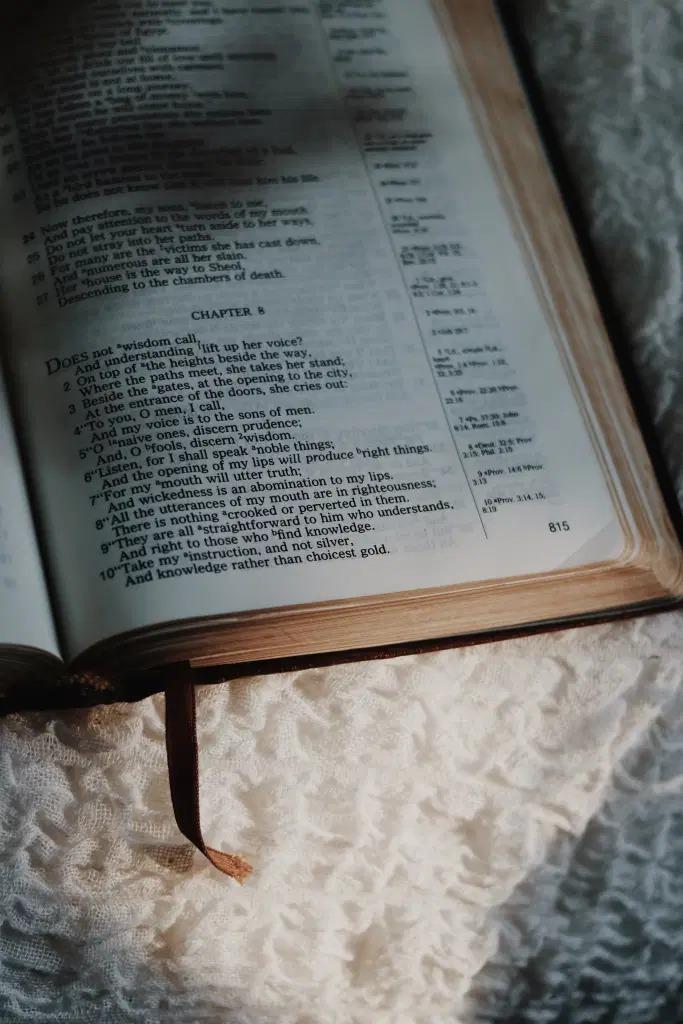
Mungkin ada di antara kita yang merasa sudah menghidupi kehidupan yang bijaksana, dimana kita memikirkan dengan matang setiap keputusan yang diambil dan berani menanggung risiko apapun yang akan menyambut di depan sana. Tapi pertanyaannya, apakah kebijaksanaan yang kita pakai itu adalah kebijaksanaan dari Allah—atau hanya berasal dari gambar diri-Nya dalam diri kita yang telah rusak? Bukankah seringkali keputusan kita justru membuat kita kecewa sendiri—bahkan menyalahkan Tuhan yang seolah-olah tidak peduli? Jika demikian, apakah kita layak untuk disebut sebagai manusia yang bijaksana? Kalaupun iya, bijaksana di mata siapa? Tidakkah kebijaksanaan yang sejati hanya bersumber dari Allah, bukannya dari manusia yang rapuh karena dosa seperti kita?
Kiranya syair dari A. M. Toplady ini menjadi perenungan kita bersama:
Nothing in my hand I bring,
Simply to Thy Cross I cling;
Naked, come to Thee for dress;
Helpless, look to Thee for grace;
Foul, I to the fountain fly;
Wash me, Saviour, or I die.[6]
Kita tahu bahwa Allah adalah Pribadi yang adil dan penuh kasih secara sempurna. Karena itu, jika ada pertanyaan mengenai kenapa-Allah-setega-itu-terhadap-manusia-sehingga-Dia-mengirimkan-air-bah-pada-zaman-Nuh (atau saat Dia menghancurkan Sodom dan Gomora), mestinya pertanyaan itu bukan ditujukan kepada Allah, tetapi kepada manusia. Kenapa manusia bisa memilih untuk sejahat itu terhadap Allah, menginjak-injak kemuliaan-Nya, meremehkan-Nya, tidak menganggap-Nya eksis, hidup semaunya, padahal mereka menerima semua hal yang baik dari Allah seumur hidup mereka? Kok manusia tega membuang Allah yang mencipta mereka menurut rupa dan gambar-Nya? Kok manusia tega menghina Allah yang menurut gambar dan rupa-Nya mereka diciptakan? Gak ada syukur dan hormatnya sama sekali! Kepada orang-orang seperti ini, apakah Allah keliru ketika Ia bersikap adil dan kasih?
—Pdt. Yuzo Adhinarta
[1] Yuval Noah Harari, Sapiens: Sejarah Ringkas Umat Manusia dari Zaman Batu hingga Perkiraan Kepunahannya, terj. Damaring Tyas Wulandari Palar (Tangerang Selatan: Kepustakaan Populer Gramedia, 2017), 6–7.
[2] Harari, Sapiens, 5.
[3] Michael Gazzaniga dkk., Psychological Science, 3 Canadian. (New York: W. W. Norton, 2012), 245.
[4] Herman Bavinck, Reformed Dogmatics (Abridged in One Volume) (Grand Rapids: Baker Academic, 2011), 311.
[5] Bavinck., Reformed Dogmatics, 347.
[6] Sinclair B. Ferguson, Kingdom Life in a Fallen World: Living Out The Sermon on the Mount (Colorado: NavPress, 1986), 33.
Untuk menjadi bagian dari gerakan generasi
muda Kristen Indonesia. Kirimkan karyamu ke: