
Asal kamu ada, aku bahagia; kita sama-sama ria.
Ada seorang yang babak-belur karena ditipu investasi bodong. Sebagian besar tabungannya habis tanpa pamrih setelah ditanamkan pada sebuah institusi abal-abal yang mengiming-iminginya dengan keuntungan besar dalam waktu singkat. Sebagian tabungannya yang lain sempat pula digunakan untuk membangun sebuah bisnis start-up yang gagal total, sampai-sampai ada hutang yang harus ditutup dengan menjual aset-aset pribadinya, yaitu rumah dan moge (motor gede) kesayangannya.
Dini hari itu, dia duduk saja di emperan sebuah komplek ruko yang gulung tikar akibat tak mampu bersaing dengan budaya bisnis daring yang marak berkembang. Wajahnya berminyak, berjerawat, akibat tak bisa tidur tiga hari. Matanya jatuh di kelopak, redup dan berkedip seperti lampu yang lupa dimatikan di teras itu. Rambutnya kusut, sekusut pikirannya yang tak mungkin diurai dengan jemarinya sendiri. Tangannya terkulai di samping tubuhnya, berharap menerima berkat atau wangsit dari langit yang menyegerakan datangnya matahari pengharapan. Di depan kakinya yang bersila lemah, terbuka selembar kertas pembungkus nasi goreng yang kaku diusap dinginnya angin Australia dua malam. Punggungnya sakit setelah bersandar sekian jam pada dinding yang dingin, yang enggan memeluknya, mengelus kepala, pundak, dan punggungnya, menenangkan dan melegakan jiwanya yang serak.

“Orang gila!” kata seorang yang wangi sendiri dalam mobilnya yang melambat saat menjumpai polisi tidur di depan ruko itu. Mata si wangi itu melirik cepat, bersama kelebat lampu mobilnya, ke arah lelaki ruko itu. Si wangi ingin segera pulang, karena jam delapan pagi itu, ada rapat di Senayan, sementara ia baru pulang setelah menerima entertainment dari seorang calon kliennya. Ia senang, meski rasa kantuk dan mabuk agak menghambatnya untuk memacu mobilnya itu.
“Gimana mau maju negara ini? Gak tahan tantangan, jadi gila, ngelantur di jalanan!”
Jalanan di depan komplek ruko itu sunyi lagi. Kelelawar sudah pulang; burung-burung belum datang. Jangan mengharapkan suara jangkrik! Hati lelaki ruko itu telah menelan semuanya. Rakus, tapi memang begitulah hati yang patah, pedih.
Tiga belas menit kemudian, saat samar matahari mulai muncul dari puncak genting, sebuah mobil melintas dengan bak belakangnya yang dijejali sejumlah orang yang berdiri dengan kain-kain lebar yang kadang-kadang berkibar dan kadang-kadang lunglai begitu saja.
“Tukang madat!” bisik orang-orang itu dengan mata yang tajam, menghakimi sekaligus menelanjangi lelaki ruko, tepat di puncak polisi tidur yang sama. Mereka hendak pergi ke Senayan, menyampaikan kegelisahan mereka tentang pelayanan pemerintah terhadap rakyat. Harga-harga barang dan jasa naik, terutama harga kain yang menjadi kostum seragam mereka, juga bendera dan bentangan yang akan mereka pamerkan bersama orasi-orasi terlatih yang akan mereka serukan nanti. Kali itu, mereka tak mengajak tukang jahit langganan mereka, yang membuat kostum, bendera, dan bentangan mereka itu, karena si tukang jahit langganan ikut-ikutan menaikkan harga jasanya.
“Gimana kita bisa maju? Ada orang macam itu, yang kerjanya mabok, terus sama negara direhab! Kita yang kerja cuma diperas buat orang-orang kayak gitu!"

Dua menit kemudian, saat burung-burung sudah menduduki kabel-kabel listrik, sebuah motor melintas, hampir melupakan adanya polisi tidur di jalan itu. Motor itu lalu berhenti di bawah sebuah pohon kesukaan anak-anak: pohon keres, kersen, talok, atau apapun namanya.
Setelah menurunkan penyangga motornya, si penunggang melepas helmnya, menyangkutkan helmnya pada kaca spion kanan motornya, lalu turun dari motornya. Ia berjalan dengan panduan matahari yang mulai berani.
Lelaki ruko itu sadar, ada orang yang mendekatinya. Telinganya rupanya masih awas mendengar langkah moderat si penunggang motor.
“Saya gak pesan kamu!” datar suara lelaki ruko itu ketika si penunggang perlahan menurunkan lutut di dekatnya.
“Baru saya mau nanya…” sahut si penunggang agak bingung. Rambutnya tergerai, diam begitu saja, karena angin yang mendadak datang hanya ada di film-film.
“Bapak ngapain di sini?” tanya si penunggang yang mendadak harus menahan napas. Lelaki ruko itu pasti belum mandi beberapa hari terakhir ini.
Lelaki ruko diam saja. Dia ingin bersikap ketus, tapi mendadak ingat ibunya yang berpesan agar dia selalu bersikap sopan. Dia menahan kentutnya. “Angin malam sialan!” umpatnya dalam hati.
Wangi. Ada wewangian yang bercampur, antara wangi sampo dan sabun mandi, juga wangi deodoran, dan jelas ketiganya tidak datang dari satu merek. Itu adalah wangi yang janggal, karena yang wangi tak seharusnya ada di jalanan. Yang wangi harusnya ada di ruang dingin yang memperbincangkan hal-hal tinggi di langit.
“Ngopi gak, Pak?” si penunggang meletakkan pantatnya di dekat lelaki ruko, lalu melepaskan panjang kakinya ke depan.
“Yah, ketinggalan…” katanya lagi, entah menyesal atau pura-pura menyesal.
Terlalu susah untuk menganalisis kejadian itu jika terlanjur dirasuk wangi yang janggal. Si penunggang mengambil telepon seluler dari kantung jaketnya, lalu mengetik pesan. Lelaki ruko diam, berusaha menikmati kentutnya yang seperti mudik ke lambungnya sendiri.
Waktu tetap berjalan, meski tanpa jam di tangan.
...
Matahari sudah telanjang. Jalanan mulai ramai. Beberapa mobil berbak terbuka sudah lewat dengan orang-orang bergaya serupa.
Sebuah motor akhirnya ikut berhenti di bawah pohon kesukaan anak-anak itu. Penunggangnya berjaket sama, turun dengan cara yang berbeda, lebih lincah, terburu-buru.
“Terima kasih ya!” kata si penunggang kepada kawannya itu. Ada sebotol logam yang diserahkan kepadanya. Tutupnya segera dibuka, lalu menyeruaklah aroma kerinduan itu: Kopi yang matang dijerang air mendidih.
Si kawan itu berdiri saja, mungkin bingung, mungkin juga kecewa karena si penunggang ternyata tak sendirian. Rambutnya keriting, sekeriting pikirannya yang belum kritis pada pagi yang baru berlabuh itu.
Kopi dituang pada tutup botol logam itu, diajukan kepada lelaki ruko.
“Kopi, Pak,” ujar si penunggang, berharap disahut oleh lelaki ruko.
Lelaki ruko menerimanya sambil mengingat kata ibunya tentang kewajiban bersikap sopan, meskipun dia sadar, perut yang terlalu lama kosong bakal menjerit ketika disiram asamnya kopi.
“Bro,” kata si penunggang kepada kawannya, “Gua kirim segini ya. Plis bantuin gua.”
Layar telepon selulernya diarahkan kepada si kawan, yang menarik-narik rambutnya yang keriting sambil berharap bisa segera memahami dengan lurus arti peristiwa itu.
Tak lama kemudian, si penunggang pergi, meninggalkan si kawan dan lelaki ruko.
...
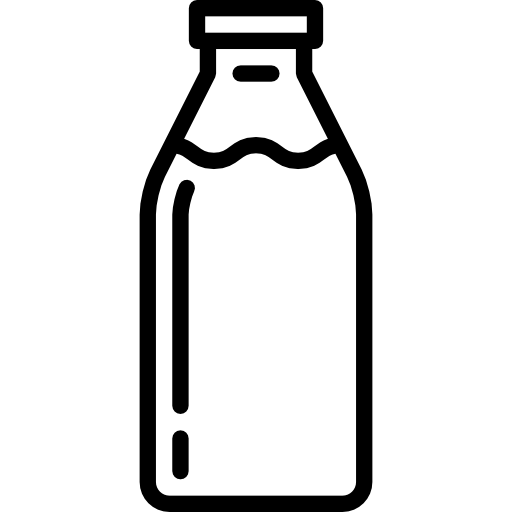
Pagi itu, kopi sebotol itu habis diminum berdua, bergantian, dengan tutup botol yang sama. Si kawan dan lelaki ruko tak banyak bertukar pandang, hanya sesekali saling melempar kata, membocorkan cerita. Mereka tahu, mereka sama-sama orang-orang yang harus menembus hari itu dengan harapan dan semangat sekalipun rasanya tanpa tujuan. Tujuan mereka cuma satu: bisa pulang. Akan tetapi, ada satu hal juga yang mereka tunggu: si penunggang.
Senayan bukan tempat mereka, bahkan mungkin bukan juga tempat nama-nama mereka diserukan, tapi menentukan diri mereka akan ditempatkan. Akan tetapi, tak selalu harus bersama Senayan untuk bisa senang. "Asal kamu ada, aku bahagia; kita sama-sama ria."
Untuk menjadi bagian dari gerakan generasi
muda Kristen Indonesia. Kirimkan karyamu ke: